Mengajar bersama menciptakan pemahaman antara pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh setempat.
Oleh Kristi Siegfried di Cox’s Bazar, Bangladesh | 20 Juli 2022
Sepanjang ingatannya, mimpi Shah Alum adalah menjadi seorang guru. Namun pendidikannya berakhir dengan tiba-tiba ketika ia terpaksa meninggalkan negara asalnya Myanmar sebelum lulus dari sekolah menengah. Di seberang perbatasan di Bangladesh, ia dan keluarganya menemukan keselamatan di sebuah kamp yang bermunculan di Cox’s Bazar, tetapi tidak ada kesempatan bagi Shah untuk menyelesaikan sekolah menengah, apalagi melanjutkan ke universitas.
Namun, hampir lima tahun kemudian, Shah, sekarang berusia 22 tahun, memimpin kelas yang terdiri dari sekitar 40 anak Rohingya yang duduk di lantai ruang kelas berbingkai bambu di kamp Kutupalong, yang menampung sekitar 750.000 pengungsi Rohingya.
Sementara Shah mengajar anak-anak Myanmar di depan kelas, Minhar Begum yang berusia 24 tahun dari komunitas Bangladesh di distrik Cox’s Bazar, berjalan di sekitar ruangan untuk memastikan semua orang mengikuti instruksi teman sekelasnya.
“Ketika kita mengajar bersama, mudah untuk mengoordinasikan kelas.”
Shah dan Manhar telah bekerja sama sebagai asisten pengajar di pusat pendidikan ini selama dua tahun terakhir. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah guru yang sepenuhnya memenuhi syarat, mereka telah menerima pelatihan UNHCR, dan di antaranya, mereka mencakup kurikulum non-formal yang sebagian besar terdiri dari keterampilan membaca dan berhitung, serta beberapa keterampilan bahasa dan kehidupan di Myanmar.
“Ketika kami mengajar bersama, mudah untuk mengoordinasikan kelas,” kata Shah. “Dia bisa di depan, mungkin menjelaskan sesuatu, dan saya bisa di belakang. Kita bisa fokus pada setiap siswa secara setara.”
Haruno Nakashiba, Koordinator Senior Perlindungan UNHCR, menjelaskan bahwa keputusan untuk menyatukan pengungsi Rohingya dan penduduk lokal Bangladesh untuk mengajar di 5.600 pusat pembelajaran di seluruh kamp di Cox’s Bazar adalah karena kebutuhan.
“Kami kekurangan guru di antara para pengungsi karena sangat sedikit orang Rohingya yang dapat menyelesaikan pendidikan tinggi mereka di Myanmar, karena pembatasan pergerakan mereka dan hak-hak lainnya,” katanya. “Jadi, untuk beberapa mata pelajaran, seperti bahasa Inggris atau matematika, kami memutuskan untuk merekrut guru dari Bangladesh. Ini juga berarti kami menciptakan lapangan kerja untuk mereka.”
Dengan Rohingya yang sebagian besar terkurung di kamp, kemitraan pendidikan ini memiliki manfaat tambahan dengan menyediakan salah satu dari sedikit kesempatan bagi pengungsi dan penduduk lokal Bangladesh untuk bertemu.
“Kami seperti saudara kandung, kami sangat memahami satu sama lain,” kata Shah tentang hubungannya dengan Munhar. “Pada awalnya, kami tidak banyak berkomunikasi, tetapi sekarang kami berbicara tentang kekuatan dan kelemahan dan bagaimana kami dapat meningkatkan.”
Bahkan dengan dukungan satu sama lain, mengajar di pusat-pusat pembelajaran bukan tanpa tantangan. Kurikulum informal dikembangkan setelah masuknya Rohingya ke Bangladesh pada tahun 2017 sebagai tindakan darurat untuk memastikan anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ini bukan pengganti pendidikan formal standar dan empat tingkatannya melayani anak-anak yang lebih muda antara usia 4 dan 14 tahun, meninggalkan kesenjangan besar dalam pendidikan bagi mereka. Anak-anak yang lebih tua.
“Ketika saya berbicara tentang tantangan yang dihadapi anak-anak, itu sama untuk saya juga,” kata Shah. “Tidak ada jalur pendidikan yang cocok di sini… Setelah lulus level 2, banyak siswa yang tidak mau kembali karena tidak memiliki sertifikat.”
Dia mengatakan banyak anak usia sekolah dasar di kamp tidak pergi ke pusat pembelajaran, dengan kehadiran menurun selama musim hujan ketika jalan di kamp menjadi berlumpur dan berbahaya. “Beberapa bekerja untuk membantu orang tua mereka; yang lain menghabiskan hari-hari mereka melakukan apa saja.”
Haruno Nakashiba dari UNHCR mengatakan UNHCR telah menyuarakan keprihatinan lama tentang kurangnya pendidikan formal di kamp-kamp dan, bersama dengan UNICEF dan mitra lainnya, telah menyerukan penggantian sistem saat ini dengan kurikulum nasional di Myanmar. Pemerintah Bangladesh setuju untuk beralih ke kurikulum Myanmar pada Januari 2020, tetapi pandemi COVID-19 telah menutup pusat pembelajaran dan menunda pengenalannya selama hampir dua tahun.
Dia akhirnya mulai menguji coba kurikulum baru akhir tahun lalu, mendaftarkan 10.000 anak di kelas enam sampai sembilan. Tahap kedua peluncuran kelas satu dan dua akan dimulai pada Juli, pada awal tahun ajaran baru, dengan sisa nilai akan diganti tahun depan sehingga semua anak usia sekolah di kamp mengikuti kurikulum Myanmar pada Juli 2023.
“Kami menginginkan kurikulum Myanmar.”
Tanpa sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Myanmar, kurikulum baru masih tidak dapat dianggap sebagai pendidikan formal, tetapi Haruno menggambarkannya sebagai hal yang penting bagi sebagian besar pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke rumah di Myanmar ketika aman untuk melakukannya.
Para pengungsi mengatakan mereka ingin membuktikan bahwa mereka milik Myanmar. Mereka berkata, “Ketika anak-anak saya belajar membaca dan menulis dalam bahasa Burma, anak-anak saya akan diakui sebagai bagian dari sana.”
Shah memberikan alasan yang sama atas ketidaksabarannya untuk mulai mengajar kurikulum baru sesegera mungkin. “Kami menginginkan kurikulum Myanmar agar anak-anak dapat melanjutkan pembelajaran mereka ketika mereka kembali ke negara mereka,” katanya.
Minhar setuju, bahkan jika itu berarti kemitraannya dengan Shah akan segera berakhir. Meskipun beberapa guru Rohingya dan Bangladesh akan terus bekerja berpasangan, guru Rohingya akan menerima pelatihan untuk mengajar sebagian besar mata pelajaran di Myanmar, sementara guru komunitas tuan rumah seperti Minhar akan fokus pada pengajaran bahasa Inggris dan membantu pelatihan.
Impian Shah suatu hari nanti menjadi guru yang berkualitas bukanlah hal yang mustahil seperti yang terlihat sebelumnya. UNHCR telah mulai memberikan pelatihan guru kepada 2.500 guru tahun ini, yang sebagian besar adalah Rohingya.
“Jika saya memiliki kesempatan untuk belajar di mana saja, saya akan melakukannya,” kata Shah. “Saya ingin pendidikan tinggi.”

“Pemikir. Fanatik internet. Penggemar zombie. Komunikator total. Spesialis budaya pop yang bangga.”

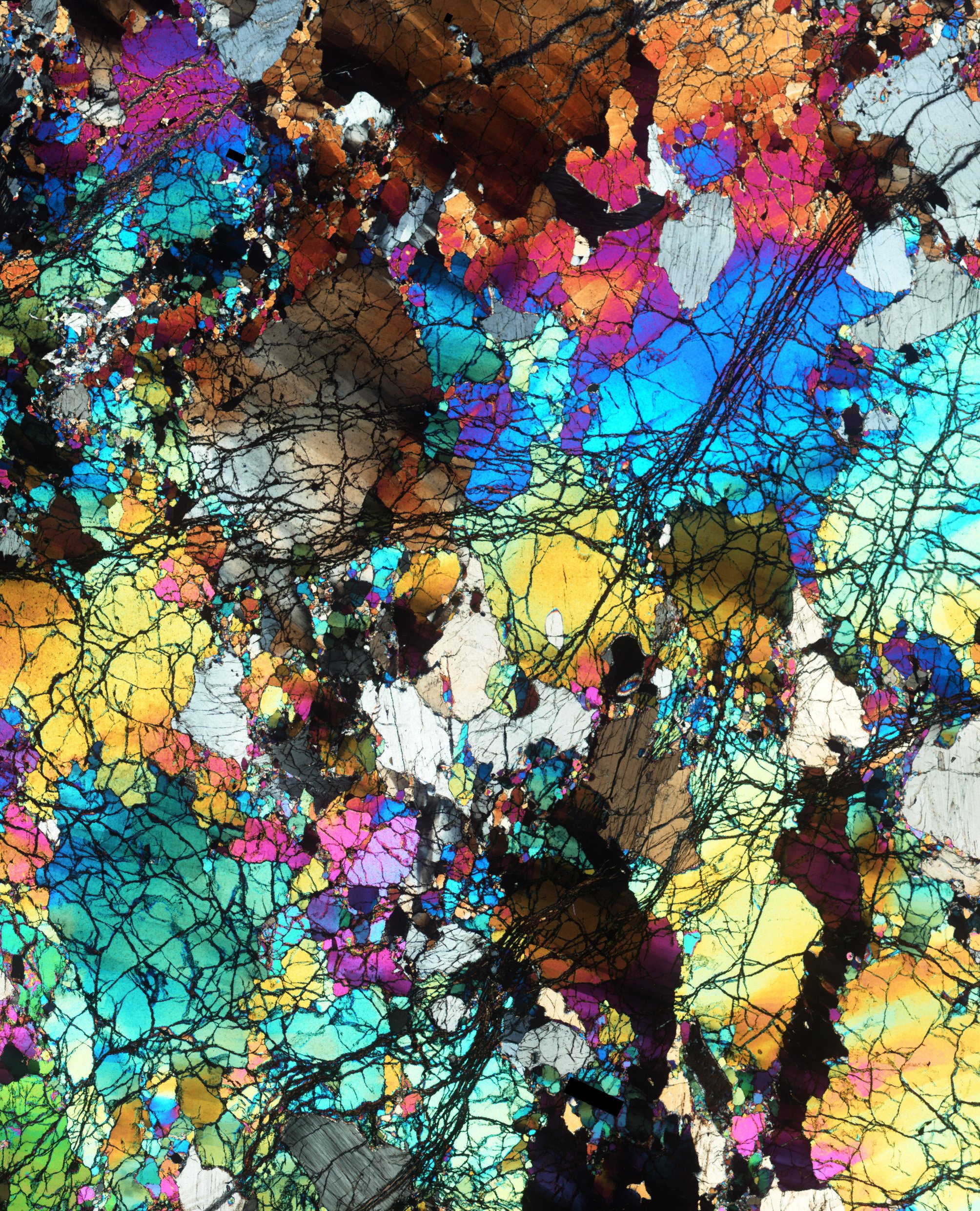




More Stories
Republik Rhode Island mempersiapkan 15 pekerja kesehatan untuk misi kemanusiaan di Gaza
Megawati Indonesia mengirimkan pesan dukungan kepada Kamala Harris dalam pemilihan presiden AS
Eropa mengaktifkan latihan Pitch Black 2024