Laut Cina Selatan adalah salah satu wilayah paling kontroversial di planet ini dengan banyak negara yang memiliki klaim teritorial atas perairan dan pulau-pulaunya. Di tengah meningkatnya agresi militer China, nasib kawasan itu telah menjadi perhatian global.
Menteri Pertahanan Rajnath Singh pada hari Rabu (23 November) berpidato di Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN di Kamboja. Dia berharap, negosiasi Code of Conduct for the South China Sea yang sedang berlangsung akan sejalan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).
Menekankan kepentingan sah India di wilayah tersebut, dia berkata, “Kami percaya bahwa prakarsa keamanan regional harus berorientasi pada penasehat dan pembangunan, untuk mencerminkan konsensus yang lebih besar… India mendukung kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan yang sah tanpa hambatan, dan damai. pemukiman di laut.” perselisihan. “
Ekspres India Itu terlihat pada perselisihan yang sudah berlangsung lama di Laut Cina Selatan dan kode etik yang akan datang di wilayah tersebut.
Apa konflik di Laut Cina Selatan?
Laut Cina Selatan terletak tepat di sebelah selatan daratan Cina dan berbatasan dengan Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Taiwan dan Vietnam. Pada awal tahun 1970-an, negara-negara ini mulai mengklaim pulau-pulau (sebagian besar tidak berpenghuni) di seberang lautan untuk mengontrol berbagai sumber daya yang dimiliki kawasan tersebut, seperti cadangan minyak yang belum dimanfaatkan, gas alam, dan daerah penangkapan ikan. Ini juga memiliki beberapa jalur pelayaran tersibuk di planet ini.
Saat ini, klaim besar-besaran China atas laut tersebut telah membuat marah negara-negara lain di wilayah tersebut. China mengklaim laut itu sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan alasan bahwa negara lain tidak berhak melakukan operasi militer atau ekonomi apa pun tanpa persetujuannya.
Negara-negara Asia Tenggara membantah klaim ini, dan pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag mengeluarkan keputusannya atas klaim yang diajukan oleh Filipina terhadap China berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Ia memenangkan Filipina dalam hampir semua hal. Namun, China, yang juga penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, telah menolak untuk mengakui otoritas pengadilan tersebut.
Citra satelit baru-baru ini di wilayah tersebut memiliki efek destabilisasi, menunjukkan upaya China untuk tidak hanya meningkatkan ukuran pulau yang ada tetapi juga membuat pulau buatan di seluruh wilayah. Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, China telah mendirikan pelabuhan, fasilitas militer, dan lapangan terbang di pulau-pulau ini—khususnya di Paracel dan Spratly, yang masing-masing memiliki dua puluh dan tujuh pos terdepan. China juga memiliterisasi Pulau Woody dengan mengerahkan jet tempur, rudal jelajah, dan sistem radar.
Untuk melindungi keseimbangan kekuatan di kawasan, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang telah membantu negara-negara Asia Tenggara dan memberi mereka bantuan militer dan ekonomi.
Apa Kode Etik untuk Laut Cina Selatan?
Pada tahun 1995, China menduduki Mischief Reef secara ilegal, hanya 210 kilometer dari pulau Palawan, Filipina. kalau tidak ASEAN Negara-negara menganggapnya sebagai upaya terang-terangan untuk mengubah status quo di wilayah tersebut.
Sebagai tanggapan, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara mengeluarkan pernyataan bersama pada tahun 1996 yang mengungkapkan keprihatinan atas situasi di Laut Cina Selatan dan menyerukan “penyelesaian damai atas perselisihan tersebut dan pengekangan oleh pihak-pihak terkait”. Selain itu, sebuah kode etik regional diusulkan, yang akan “meletakkan dasar bagi stabilitas jangka panjang di kawasan ini dan mendorong saling pengertian di antara negara-negara penggugat”.
Setelah bertahun-tahun negosiasi yang menyakitkan antara ASEAN dan China, Deklarasi Perilaku (DOC) yang tidak mengikat dan ambisius di Laut China Selatan tercapai pada tahun 2002. Hal ini seharusnya menjadi batu loncatan penting untuk menciptakan kode etik yang mengikat yang akan menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan. Namun, China terus menduduki lebih banyak pulau dan melakukan aktivitas militer, mendorong negara-negara ASEAN untuk mengungkapkan keprihatinan tentang kedaulatan dan kepentingan mereka.
Selama 20 tahun terakhir, ini telah menjadi kenyataan di wilayah tersebut. Di satu sisi, setiap upaya untuk menghasilkan kode etik yang mengikat telah diblokir oleh China. Di sisi lain, ia melanjutkan kebijakan ekspansionisnya yang membuat kawasan ini sangat bergejolak.
Menurut Ian Storey, rekan senior di Institut ISEAS-Yusof Ishak di Singapura, ada tiga masalah utama yang menghambat kemajuan menuju kode etik.
Buku Bertingkat Kebijakan luar negeri“Pertama, apa ruang lingkup geografis dari perjanjian itu? Haruskah mencakup Kepulauan Paracel, seperti yang diinginkan Vietnam tetapi tidak diinginkan China, atau Beting Scarborough, seperti yang diinginkan Filipina tetapi tidak diinginkan China. Kedua, COC harus [code of conduct] Sertakan daftar yang harus dan tidak boleh dilakukan? Beijing tidak akan mau mengikat tangannya untuk menyetujui pelarangan kegiatan ini. Ketiga, apakah COC harus mengikat secara hukum? Sebagian besar negara anggota ASEAN tampaknya mendukung ini, tetapi China menentangnya.”
Beberapa perkembangan terakhir
Pada Mei 2017, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Tiongkok mengadopsi kerangka kerja Kode Etik di Laut China Selatan dengan tujuan “memfasilitasi pekerjaan menuju kesimpulan kode etik yang efektif sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama”. Setahun kemudian, kesepakatan dicapai pada satu draf kode etik untuk Laut Cina Selatan (SDNT). Sementara beberapa menganggap momen penting, yang lain lebih berhati-hati dalam menilainya.
Posisi China dalam SDNT didasarkan pada pengakuan sembilan garis putus-putus, yaitu garis yang menunjukkan klaim teritorial China, termasuk sebagian besar Laut China Selatan. Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase yang dibentuk di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menemukan bahwa klaim China atas hak historis atas wilayah laut (berlawanan dengan daratan darat dan perairan teritorial) dalam garis sembilan putus tidak memiliki efek hukum jika itu melebihi apa yang menjadi haknya di bawah UNCLOS.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara di luar wilayah tersebut, menyerukan kepada ASEAN dan China untuk memastikan bahwa kode etik tersebut “konsisten dengan hukum internasional yang ada, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.” Menyimpang dari UNCLOS saat membuat Kode Etik dapat membuka sekaleng cacing tidak hanya di Laut Cina Selatan tetapi juga di seluruh dunia, di mana pun ada sengketa teritorial atau maritim.
Menurut Kapten Raul Pedrozo (Purn.), Profesor Hukum Internasional di US Naval War College, China yang tiba-tiba terburu-buru untuk menyelesaikan Kode Etik berada di belakang keberhasilannya dalam mengambil kendali atas dasar Spratly dan memiliterisasi Scarborough Shoal dan Kepulauan Paracel. Ini telah mengubah status quo sedemikian rupa sehingga “tidak ada ruginya dan segalanya diperoleh dengan menyimpulkan kode etik yang memajukan klaimnya dan memajukan keamanan nasional dan kepentingan ekonominya di LCS, semuanya dengan mengorbankan ASEAN dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”, dia menulis dalam Jurnal Hukum Studi Hukum Internasional.
Komentar Rajnath Singh datang dalam konteks ini karena negara-negara seperti India, Amerika Serikat dan Jepang memperingatkan ASEAN bahwa kode etik hanya akan menguntungkan China. Dalam kata-kata Kapten Pedrozo, “Apakah para diplomat ASEAN akan begitu terobsesi dengan membuat kode etik palsu sehingga mereka akan kehilangan objektivitas dan menerima kesepakatan yang buruk daripada tidak ada kode sama sekali?”

“Pemikir. Fanatik internet. Penggemar zombie. Komunikator total. Spesialis budaya pop yang bangga.”

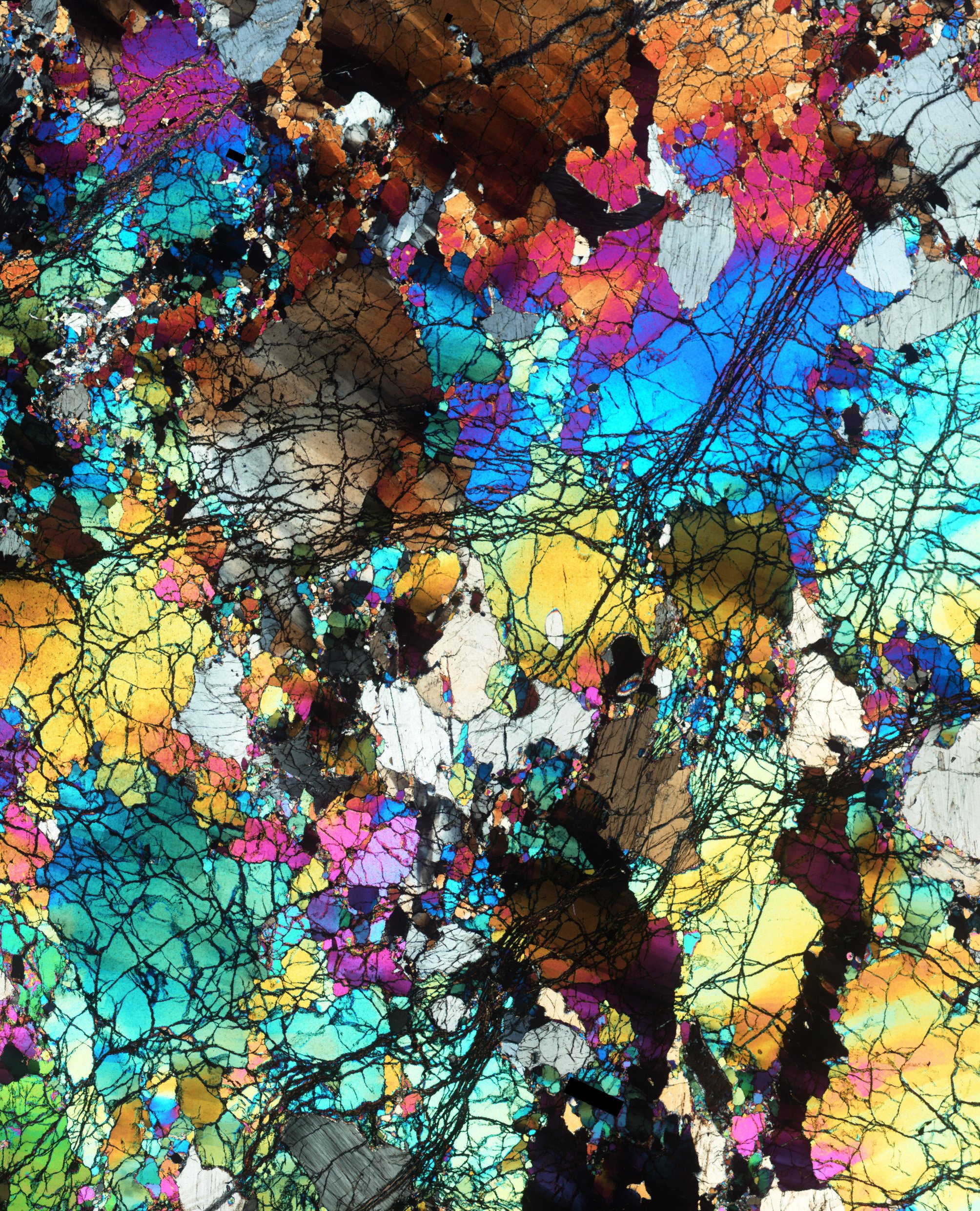




More Stories
Republik Rhode Island mempersiapkan 15 pekerja kesehatan untuk misi kemanusiaan di Gaza
Megawati Indonesia mengirimkan pesan dukungan kepada Kamala Harris dalam pemilihan presiden AS
Eropa mengaktifkan latihan Pitch Black 2024